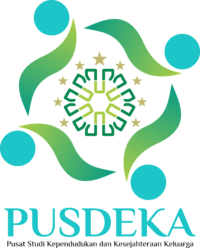Oleh: Rindang Farihah
Pada Juli 2019 nama Tengku Munirwan tiba-tiba banyak dibicarakan. Kepala desa asal Aceh Utara itu dijadikan tersangka oleh Polda Aceh. Musababnya, Munirwan dianggap memperjualbelikan benih padi yang belum bersertifikasi. Padahal, benih tersebut dikembangkan dari bantuan Presiden ketujuh RI Joko Widodo. Bahkan, masyarakat setempat menamai benih IF8 itu sebagai ‘benih padi Jokowi’.
Benih padi Jokowi bukan sembarang benih. Di tangan Munirwan, benih tersebut mampu menjelma sebagai ‘Dewi Nawangwulan’ yang melipatgandakan hasil pertanian. Jika benih biasa hanya sanggup memproduksi 8 ton sekali panen, benih padi Jokowi sanggup menghasilkan 11 ton. Benih itu pun dianggap lebih tahan dari berbagai kondisi dan cuaca. Namun kenapa Munirwan sampai ditahan?
Untuk membincangkannya kita bisa berkenalan dengan sosok Vandana Shiva, seorang aktivis lingkungan sekaligus ilmuwan asal India. Ia secara terang-terangan menentang praktek globalisasi pertanian yang marak pada tahun 1970-an. Dia juga mengkritik keberadaan lembaga-lembaga bantuan dunia yang kedatangannya secara sekaligus berperan aktif mendukung aksi perampasan sumber daya negara-negara berkembang.
Vandana Shiva lahir di Dehradun pada 1952. Secara keilmuwan, ia adalah ahli dalam bidang fisika. Namun ia sangat menaruh perhatian pada lingkungan. Salah satu gagasan pentingnya adalah menentang revolusi hijau dan ekonomi hijau. Mengapa Shiva begitu kuat dalam menentang konsep ‘hijau’ yang saat itu sedang disuarakan oleh banyak pihak? Tak lain adalah karena revolusi hijau yang banyak dibicarakan mengancam banyak sektor, termasuk pertanian.
Dalam jargon ‘hijau’ terdapat industrialisasi pertanian yang membuat pertanian mengalami berbagai bentuk kapitalisasi. Padahal, pertanian merupakan landasan awal peradaban manusia. Aktivitas pertanian adalah mengelola sumber daya alam untuk dimanfaatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Namun seiring perkembangan teknologi, hal tersebut justru digunakan untuk kepentingan bisnis dengan cara memproduksi bahan makanan dalam skala jumbo. Pertanian bukan lagi untuk mencukupi kebutuhan manusia, namun sudah berubah sebagai sarana meraih keuntungan.
Industrialisasi dan kapitalisasi pertanian memberikan dampak yang mengerikan bagi alam dan kelompok rentan. Praktek industri pertanian merugikan petani kecil karena kerap berhadap-hadapan dengan korporasi dan oligarki. Industrialisasi ini kemudian menciptakan ketergantungan petani pada pupuk kimia, pestisida, bahan bakar fosil, dan pasokan air yang dikomodifikasi sedemikian rupa. Selain itu, industrialisasi menyebabkan adanya alih fungsi hutan dalam sekala besar di berbagai belahan dunia.
Di Indonesia, ada banyak kasus di mana masyarakat adat mengalami perampasan ruang hidup yang membuat kritik Shiva pada revolusi hijau mendapatkan konteksnya. Berbagai megaproyek pertanian yang mengatasnamakan swasembada pangan seperti food estate mengorbankan jutaan hektar hutan di Kalimantan dan Papua. Belum lagi kasus Munirwan yang saya singgung di awal tulisan ini yang sarat akan kepentingan kapital. Jika seorang petani mampu menemukan atau mengembangkan benih yang melipatgandakan hasil, mengapa tidak didukung? Apalagi alasan penangkapan adalah karena benih tersebut tidak tersertifikasi.
Sertifikasi, paten, dan sejenisnya ini juga menjadi kritik sentral Shiva. Bagi Shiva, benih tidak boleh dipatenkan. Sebab benih adalah unsur fundamental dalam aktivitas pertanian. Jika benih dipatenkan, bagaimana aktivitas pertanian bisa memiliki keberlanjutan? Untuk merealisasikan ide-idenya, Shiva melakukan gerakan penyelamatan benih dan membentuk perusahaan Navdanya pada 1991. Pendirian perusahaan ini bertujuan untuk melindungi keanekaragaman benih asli melalui promosi pertanian organik dan perdagangan yang adil. Mereka membagikan benih secara gratis kepada para petani yang kemudian mereka berkomitmen menyimpan kembali benih tersebut dan sebagian lainnya dibagi kepada petani lain.
Melalui perusahaan ini Shiva menentang perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan (TRIPS) WTO 1994. TRIPS ini adalah biang kerok atas izin penerbitan paten untuk makhluk hidup. Dia mengutuk praktik mematenkan bentuk kehidupan dengan menyebutnya sebagai ‘biopiracy’ dan melawan upaya-upaya paten lainnya seperti beras basmati. Beras basmati salah satu pangan pokok warga India. Namun seiring berjalannya waktu ada pihak-pihak yang ingin mematenkannya. Pada tahun 2011 didirikan anak perusahaan Navdanya di Italia untuk memperluas jangkauan global.
Ekofeminisme
Shiva disebut sebagai salah satu tokoh kunci dalam gerakan ekofeminisme dunia. Ekofeminisme merupakan gerakan yang menentang ideologi patriarki yang mendominasi dan mengeksploitasi perempuan dan alam yang berakhir dengan kekerasan. Gerakan ini berfokus pada pengelolaan alam, hutan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan prinsip keadilan lingkungan, kesetaraan gender, kemandirian lokal, dan kebijakan yang berkelanjutan. Melalui gerakan ini, Shiva menganjurkan pendekatan pertanian yang berpusat pada perempuan di India untuk hasil yang lebih produktif. Ia percaya bahwa melibatkan perempuan dalam pekerjaan lingkungan akan memberikan dampak positif bagi bumi.
Pemikiran dan gerakan Vandana Shiva mempengaruhi gerakan ekofeminisme lainnya. Sebagai contoh, gerakan Chipko di India dan gerakan Green Belt di Afrika. Kedua gerakan ini berfokus pada pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Jika Chipko menggunakan strategi unik berupa aksi “memeluk pohon” untuk mencegah penebangan pohon, maka gerakan Green Belt melakukan penanaman pohon dan menghindarkan dari kerusakan alam.
Bagaimana dengan Indonesia? Dalam beberapa tahun belakangan, ekofeminisme sudah mulai banyak dikaji dan dipraktikkan melalui hadirnya perempuan sebagai subjek penyelamatan lingkungan. Salah satu contoh bagaimana perempuan Indonesia melakukan upaya penyelamatan lingkungan ialah melalui gerakan para perempuan Kendeng, Pati. Para perempuan turut bergerak untuk menolak pembangunan semen di pegunungan Kendeng yang mengancam sumber daya kehidupan mereka. Beberapa aksi yang dilakukan antara lain dengan menyemen kaki mereka di depan Istana Presiden. Aksi ini kemudian juga dilakukan di depan kantor balai kota Heidelberg, Jerman, di mana perusahaan semen asal kota itu memiliki saham mayoritas PT Indocement, perusahaan semen yang akan menambang pegunungan Kendeng.
Mungkin apa yang dilakukan oleh para perempuan Kendeng tidak terkait langsung dengan ide dan gagasan Shiva. Namun keduanya memberi kita sebuah konsep penyadaran bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam merawat alam ini. Sebab, sebagaimana Shiva pernah katakan, “Di segenggam tanah ini terdapat masa depanmu. Rawatlah ia, dan ia akan merawatmu. Hancurkanlah ia, dan ia akan menghancurkanmu.”
Pada Juli 2019 nama Tengku Munirwan tiba-tiba banyak dibicarakan. Kepala desa asal Aceh Utara itu dijadikan tersangka oleh Polda Aceh. Musababnya, Munirwan dianggap memperjualbelikan benih padi yang belum bersertifikasi. Padahal, benih tersebut dikembangkan dari bantuan Presiden ketujuh RI Joko Widodo. Bahkan, masyarakat setempat menamai benih IF8 itu sebagai ‘benih padi Jokowi’.
Benih padi Jokowi bukan sembarang benih. Di tangan Munirwan, benih tersebut mampu menjelma sebagai ‘Dewi Nawangwulan’ yang melipatgandakan hasil pertanian. Jika benih biasa hanya sanggup memproduksi 8 ton sekali panen, benih padi Jokowi sanggup menghasilkan 11 ton. Benih itu pun dianggap lebih tahan dari berbagai kondisi dan cuaca. Namun kenapa Munirwan sampai ditahan?
Untuk membincangkannya kita bisa berkenalan dengan sosok Vandana Shiva, seorang aktivis lingkungan sekaligus ilmuwan asal India. Ia secara terang-terangan menentang praktek globalisasi pertanian yang marak pada tahun 1970-an. Dia juga mengkritik keberadaan lembaga-lembaga bantuan dunia yang kedatangannya secara sekaligus berperan aktif mendukung aksi perampasan sumber daya negara-negara berkembang.
Vandana Shiva lahir di Dehradun pada 1952. Secara keilmuwan, ia adalah ahli dalam bidang fisika. Namun ia sangat menaruh perhatian pada lingkungan. Salah satu gagasan pentingnya adalah menentang revolusi hijau dan ekonomi hijau. Mengapa Shiva begitu kuat dalam menentang konsep ‘hijau’ yang saat itu sedang disuarakan oleh banyak pihak? Tak lain adalah karena revolusi hijau yang banyak dibicarakan mengancam banyak sektor, termasuk pertanian.
Dalam jargon ‘hijau’ terdapat industrialisasi pertanian yang membuat pertanian mengalami berbagai bentuk kapitalisasi. Padahal, pertanian merupakan landasan awal peradaban manusia. Aktivitas pertanian adalah mengelola sumber daya alam untuk dimanfaatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Namun seiring perkembangan teknologi, hal tersebut justru digunakan untuk kepentingan bisnis dengan cara memproduksi bahan makanan dalam skala jumbo. Pertanian bukan lagi untuk mencukupi kebutuhan manusia, namun sudah berubah sebagai sarana meraih keuntungan.
Industrialisasi dan kapitalisasi pertanian memberikan dampak yang mengerikan bagi alam dan kelompok rentan. Praktek industri pertanian merugikan petani kecil karena kerap berhadap-hadapan dengan korporasi dan oligarki. Industrialisasi ini kemudian menciptakan ketergantungan petani pada pupuk kimia, pestisida, bahan bakar fosil, dan pasokan air yang dikomodifikasi sedemikian rupa. Selain itu, industrialisasi menyebabkan adanya alih fungsi hutan dalam sekala besar di berbagai belahan dunia.
Di Indonesia, ada banyak kasus di mana masyarakat adat mengalami perampasan ruang hidup yang membuat kritik Shiva pada revolusi hijau mendapatkan konteksnya. Berbagai megaproyek pertanian yang mengatasnamakan swasembada pangan seperti food estate mengorbankan jutaan hektar hutan di Kalimantan dan Papua. Belum lagi kasus Munirwan yang saya singgung di awal tulisan ini yang sarat akan kepentingan kapital. Jika seorang petani mampu menemukan atau mengembangkan benih yang melipatgandakan hasil, mengapa tidak didukung? Apalagi alasan penangkapan adalah karena benih tersebut tidak tersertifikasi.
Sertifikasi, paten, dan sejenisnya ini juga menjadi kritik sentral Shiva. Bagi Shiva, benih tidak boleh dipatenkan. Sebab benih adalah unsur fundamental dalam aktivitas pertanian. Jika benih dipatenkan, bagaimana aktivitas pertanian bisa memiliki keberlanjutan? Untuk merealisasikan ide-idenya, Shiva melakukan gerakan penyelamatan benih dan membentuk perusahaan Navdanya pada 1991. Pendirian perusahaan ini bertujuan untuk melindungi keanekaragaman benih asli melalui promosi pertanian organik dan perdagangan yang adil. Mereka membagikan benih secara gratis kepada para petani yang kemudian mereka berkomitmen menyimpan kembali benih tersebut dan sebagian lainnya dibagi kepada petani lain.
Melalui perusahaan ini Shiva menentang perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan (TRIPS) WTO 1994. TRIPS ini adalah biang kerok atas izin penerbitan paten untuk makhluk hidup. Dia mengutuk praktik mematenkan bentuk kehidupan dengan menyebutnya sebagai ‘biopiracy’ dan melawan upaya-upaya paten lainnya seperti beras basmati. Beras basmati salah satu pangan pokok warga India. Namun seiring berjalannya waktu ada pihak-pihak yang ingin mematenkannya. Pada tahun 2011 didirikan anak perusahaan Navdanya di Italia untuk memperluas jangkauan global.
Ekofeminisme
Shiva disebut sebagai salah satu tokoh kunci dalam gerakan ekofeminisme dunia. Ekofeminisme merupakan gerakan yang menentang ideologi patriarki yang mendominasi dan mengeksploitasi perempuan dan alam yang berakhir dengan kekerasan. Gerakan ini berfokus pada pengelolaan alam, hutan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan prinsip keadilan lingkungan, kesetaraan gender, kemandirian lokal, dan kebijakan yang berkelanjutan. Melalui gerakan ini, Shiva menganjurkan pendekatan pertanian yang berpusat pada perempuan di India untuk hasil yang lebih produktif. Ia percaya bahwa melibatkan perempuan dalam pekerjaan lingkungan akan memberikan dampak positif bagi bumi.
Pemikiran dan gerakan Vandana Shiva mempengaruhi gerakan ekofeminisme lainnya. Sebagai contoh, gerakan Chipko di India dan gerakan Green Belt di Afrika. Kedua gerakan ini berfokus pada pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Jika Chipko menggunakan strategi unik berupa aksi “memeluk pohon” untuk mencegah penebangan pohon, maka gerakan Green Belt melakukan penanaman pohon dan menghindarkan dari kerusakan alam.
Bagaimana dengan Indonesia? Dalam beberapa tahun belakangan, ekofeminisme sudah mulai banyak dikaji dan dipraktikkan melalui hadirnya perempuan sebagai subjek penyelamatan lingkungan. Salah satu contoh bagaimana perempuan Indonesia melakukan upaya penyelamatan lingkungan ialah melalui gerakan para perempuan Kendeng, Pati. Para perempuan turut bergerak untuk menolak pembangunan semen di pegunungan Kendeng yang mengancam sumber daya kehidupan mereka. Beberapa aksi yang dilakukan antara lain dengan menyemen kaki mereka di depan Istana Presiden. Aksi ini kemudian juga dilakukan di depan kantor balai kota Heidelberg, Jerman, di mana perusahaan semen asal kota itu memiliki saham mayoritas PT Indocement, perusahaan semen yang akan menambang pegunungan Kendeng.
Mungkin apa yang dilakukan oleh para perempuan Kendeng tidak terkait langsung dengan ide dan gagasan Shiva. Namun keduanya memberi kita sebuah konsep penyadaran bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam merawat alam ini. Sebab, sebagaimana Shiva pernah katakan, “Di segenggam tanah ini terdapat masa depanmu. Rawatlah ia, dan ia akan merawatmu. Hancurkanlah ia, dan ia akan menghancurkanmu.”
Rindang Farihah merupakan Direktur Pusat Studi Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga (PUSDEKA) Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta