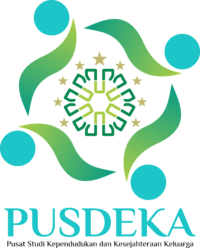Oleh: Nabilah Munsyarihah
Pekan lalu, telah terselenggara Kongres Keluarga Maslahat NU dalam rangkaian Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama. Salah satu yang bagi saya paling menarik adalah sesi panel Keluarga Terdidik. Topik ini merupakan salah satu dari enam program strategis GKMNU.
Dalam sesi tersebut, salah satu narasumber, Elga Andriana, PhD dari Fakultas Psikologi, UGM, menyampaikan kuadran gaya parenting. Di antaranya, abai, permisif, otoritarian, dan otoritatif.
Kita akan menyinggung dua gaya yang terakhir saja untuk membedakan otoritarian dan otoritatif. Gaya pengasuhan otoritarian artinya orang tua tidak memberikan ruang pada anak untuk mengambil keputusan dalam keluarga bahkan untuk dirinya sendiri. Gaya pengasuhan seperti ini kerap membuat anak tertekan karena terus menerus merasa terpaksa. Bu Elga mencontohkan kasus seorang mahasiswa yang menghilang dan memutus hubungan dengan orang tua karena tiba-tiba kucingnya lenyap setelah dianggap sebagai penghambat skripsinya.
Secara kronologis, kasus ini tampaknya hanya dipicu perkara kucing. Namun sebenarnya hal seperti itu berulang terjadi. Saat ia merasa bisa mandiri, dia pun mengambil keputusan besar dan ekstrem; menghilang dan memutus hubungan dengan orang tua. Dalam kasus lain, anak-anak yang putus asa bahkan bisa berakhir bunuh diri.
Dr. Ela menyampaikan kata kunci penting yaitu agensi. Mudahnya agensi itu menumbuhkan keberanian dan inisiatif untuk mengambil keputusan baik untuk diri sendiri maupun secara sosial. Anak yang dilatih mengambil keputusan yaitu dengan memilih dan mempertimbangkan konsekuensi akan tumbuh sebagai manusia yang memiliki agensi. Di masa depan, karakter anak seperti ini punya bekal menjadi pemimpin.
Lalu bagaimana agensi dalam pengasuhan digital? Perkara hape kerap kali menjadi sumber konflik dalam keluarga. Hape dituding sebagai sumber berbagai masalah mulai dari gangguan emosi, gangguan perilaku, kencanduan, kecemasan, speech delay, dan sebagainya.
Jika memberlakukan agensi, apa anak-anak bisa memutuskan atas sesuatu yang bisa jadi membawa risiko bagi mereka?
Internet memang bagai hutan rimba. Dunia nyata pun sebenarnya tak kalah berisikonya. Melepaskan anak berangkat sendiri ke sekolah dengan jalan kaki, bersepeda atau naik kendaraan umum tentu mengandung risiko. Sebelum kita membiarkan mereka berangkat sendiri, kita lebih dulu menemani mereka berangkat, menunjukkan rute yang benar, mengajari cara pergi yang aman, jika ada bahaya dari kendaraan atau orang asing kita ajari cara menghindar dan meminta tolong.
Tidak jauh berbeda, seperi itu pula yang seharusnya kita lakukan dalam pengasuhan digital. Kita sebagai orang tua lebih dulu tahu isi internet, memetakan risiko, memberi tau aplikasi sesuai usia, dan menavigasi anak untuk menghindari atau mengatasi risiko.
Setelah membaca buku Parenting for a Digital Future karya Prof. Sonia Livingstone dari London School of Economics, saya menyadari bahwa tips-tips yang bersliweran di sosial media itu tidak bisa menjawab situasi semua keluarga. Itu bisa membantu, namun keragaman keluarga tidak bisa direspon dengan tips yang terkesan mensimplifikasi.
Mengatur dan membatasi durasi, aplikasi, konten dan sebagainya hanya mungkin terjadi dengan damai jika sejak awal orang tua menjalankan gaya otoritatif dan menumbuhkan agensi anak. Karena jika gaya ini sudah menjadi kebiasaan, anak-anak akan bisa diberikan arahan yang masuk akal bagi mereka, bisa berkompromi, dan menilai sendiri mana yang aman dan mana yang berisiko. Tanpa obrolan, yang ada hanya instruksi bahkan bentakan. Anak marah dan orang tua frustrasi.
Tapi, selain gaya otoritatif dalam pengasuhan digital mensyaratkan satu hal lagi yaitu kompetensi. Seperti yang sudah saya sebut di atas, kemampuan orang tua dalam keterampilan dan keamanan digital yang bisa menjadi pilar dalam pengasuhan masa kini. Dengan demikian, keragaman minat anak yang berbeda-beda dapat direspon sesuai situasi keluarga. Ini memungkinkan kombinasi peraturan yang berbeda antara satu keluarga dengan yang lain.
Jika orang tua belum cukup cakap atau kalah cakap dibanding anak-anak, ini yang harus diintrospeksi dalam diri orang tua. Jika tidak tahu cara menggunakan dan tidak tahu peta, bagaimana bisa mengelola?
Pertanyaan selanjutnya yang lebih serius, memberdayakan orang tua Indonesia dalam literasi digital itu tanggung jawab siapa? Sementara problem di masyarakat karena lemahnya literasi digital keluarga sudah di titik sangat mengkhawatirkan. Apakah negara ini benar-benar punya instrumen yang menyentuh keluarga sebagai institusi terkecil masyarakat? Bukan membagi anggota keluarga dalam angka statistik lain, anak sebagai siswa dan orang tua sebagai pekerja. Apakah ada? Atau keluarga harus menyelesaikan persoalan ini sendiri?
Nabilah Munsyarihah, Direktur Alala Kids, Mahasiswa Program Magister Ilmu Komunikasi UGM